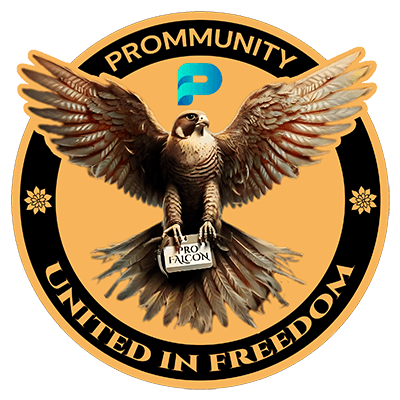Dalam hidup ini, kita semua pernah berdiri di persimpangan besar—memilih satu jalan dan merelakan banyak kemungkinan lain. Malam itu, di tengah lingkaran Pro’s, saya mendengar kisah Pro Miswanto (Pro Wanto), Pro Leader Nanik, dan Capt Paul tentang keputusan-keputusan besar yang mereka ambil. Ada keputusan yang mengguncang kenyamanan, seperti menolak kerja tetap dengan gaji lembur demi waktu bersama anak-anak. Itu bukan keputusan kecil. Itu keputusan yang membela suara hati—bukan sekadar mengejar angka.
Pertanyaan itu pun pulang ke dada saya:
Suara siapa yang paling sering saya dengarkan saat mengambil keputusan penting—ego, atau intuisi?
Saat Angka Menggantikan Doa

Sejak lulus sekolah, saya menjadi tulang punggung keluarga—menanggung kebutuhan lima orang. Secara logika, saya hitung: untuk hidup layak, minimal 5 juta per bulan. Untuk punya rumah, saya kira butuh 15 juta per bulan. Maka kepala saya penuh strategi: kejar skill, proyek apa saja saya ambil, konsultasi teknis ke Coach Farlodrian — The Mind Upgrader. Urusan spiritual? Jujur, saya tolak. “Kalau mau rezeki ya kerja keras. Berdoa itu harus tulus, bukan minta angka.” Begitu pikir saya waktu itu.
Kerja keras berbuah: saya mencicipi income dua digit saat masih kuliah—belum 15 juta, tapi hampir. Fleksibel pula: kuliah jalan, aktif di Prommunity, keluarga tertopang. Tapi kebutuhan tak henti bertambah. Ambisi naik lagi: target 100 juta dalam 4 bulan. Rencana saya: jual e-book 100 ribu ke 1.000 orang—masuk akal di kertas.
Lalu semesta “mengetuk”: tiba-tiba ada prospek komisi 100 juta dari order AC 1.000 unit (dari produk klien, di luar fee jasa). Tapi saya tak pernah buka Tokopedia—pelanggan sudah beli di tempat lain. Hangus.
Pelajarannya menohok: strategi itu penting, tapi tanpa hening—tanpa ruang untuk intuisi—kita mudah tersandung di pintu yang sudah terbuka.
Ketika Ego Menyamar Jadi Peduli

Saya kira semua itu demi keluarga. Nyatanya, ada sisi diri yang ingin diakui, disanjung, dibanggakan. Kejar angka, tambah target, makin kencang. Sampai suatu titik, saya lelah: capek, pusing, ingin menyerah, bahkan sempat merasa ingin mengakhiri semuanya. Di momen paling berat itu, nasihat Coach Farlo menancap:
“Dunia jangan ditaruh di atas kepala, tapi kita dudukin. Kalau ditaruh di atas kepala, ya berat“
Kalimat sederhana itu meruntuhkan benteng ego. Untuk pertama kalinya, saya pasrah total kepada Tuhan. Saya mulai rutin Kontemplasi, Doa, Materialisasi. Saya tetap bergerak, tetapi dari tenang—bukan dari dikejar ambisi.
Jalan yang Tidak Populer, Namun Damai

Di akhir 2024, saya tulis keinginan untuk 2025: keluarga kembali kumpul, ekonomi aman dan mandiri—tidak hanya bergantung pada saya. Saya sempat membayangkan skenarionya: memboyong semua ke Surabaya, memberi modal usaha, memantau. Nyatanya, jalannya berbeda.
Ujian datang bertubi: nenek sakit, biaya pengobatan, konflik keluarga, bahkan terusir dari rumah nenek buyut karena persoalan warisan. Lalu puncaknya saat Pro Congress bulan Mei: nenek wafat. Hati saya pecah, adik bungsu sakit-sakitan, sempat kecelakaan. Saya nyaris kosong—sampai akhirnya, di percakapan tentang spiritual yang dibukakan Coach Farlo, saya benar-benar menangis. Lama. Dan dibiarkan.
Justru dari situ, mujizat turun dengan cara yang tak saya duga: keluarga dipertemukan kembali di Kalimantan. Kebutuhan kembali seperti masa saya SD–SMP: cukup, tenang, terpenuhi. Saya tidak lagi menjadi penopang utama. Doa saya—keluarga berkumpul dan ekonomi aman—dikabulkan, lewat jalan yang tidak terpikirkan.
Butuh sembilan tahun (2016–2025) sejak masa bangkrut SMP sampai saya melihat kebulatan ujung kisah ini. Tanpa jalan terjal itu, mungkin saya tak akan belajar pengembangan diri, digital marketing, bisnis, dan tak akan bertemu Anda semua di Prommunity.
Ternyata, seringkali kita hanya perlu: memerangi ego dan hawa nafsu—lalu berpasrah.
Membedakan Ego vs Intuisi (Empat Dimensi)

Sumber
Ego: lahir dari takut, luka lama, ambisi, haus pengakuan—rasa “belum cukup”.
Intuisi: muncul dari kedamaian, kebijaksanaan batin, relasi jiwa dengan Tuhan.
Energi
Ego: keras, tergesa, memaksa; “harus sekarang” dan menimbulkan cemas.
Intuisi: lembut, konsisten, tidak memaksa; menimbulkan tenang meski keputusan berat.
Motivasi
Ego: ingin menang, unggul, membuktikan diri; logika kompetisi.
Intuisi: mengikuti kebenaran batin; sering tidak populer, tapi terasa benar.
Dampak Jangka Panjang
Ego: sering meninggalkan penyesalan, lelah, dan rasa terjebak.
Intuisi: awalnya mungkin berat, namun menumbuhkan damai dan ringan.
Tanda Praktis: Ini Ego atau Intuisi?

Tempo: buru-buru & takut tertinggal = ego; lapang & tak gentar waktu = intuisi.
Sensasi tubuh: tegang di rahang/dada = ego; napas panjang & hangat di dada = intuisi.
Dialog batin: “kalau gak sekarang gue kalah” = ego; “jalan ini benar meski sunyi” = intuisi.
Relasi: ego membuat saya ingin dikagumi; intuisi membuat saya ingin bermanfaat.
Buahnya: ego memuaskan instan; intuisi menumbuhkan makna.
Red Flags Keputusan dari Ego
- Saya takut dinilai gagal sehingga ingin cepat-cepat “membuktikan”.
- Saya mengabaikan sinyal tubuh (sesak, pusing) demi target.
- Saya meremehkan doa/hening karena “tidak produktif”.
- Semua skenario saya bergantung pada kontrol saya sendiri.
Pelajaran Kunci dari Perjalanan Saya

Strategi perlu; hening wajib. Pintu besar bisa terlewat kalau kita tidak berhenti untuk mendengar.
Pasrah bukan pasif. Saya tetap bergerak—tapi dari damai, bukan dari panik.
Tuhan menyiapkan jalan, sering kali bukan yang saya rancang.
Waktu adalah guru. Sembilan tahun ditempa, agar yang tumbuh bukan hanya hasil, tetapi jiwa.
Epilog: Dudukilah Dunia, Jangan Dipanggul

Hari ini, ketika saya bimbang, saya memilih tenang. Saya pilih memeluk sunyi sampai suara jiwa terdengar. Saya percaya: keputusan terbaik bukan yang paling keras berteriak, melainkan yang paling jujur menuntun langkah. Dan bila Anda sedang di persimpangan, semoga kerangka kecil ini membantu Anda menata hati—agar Anda tidak sekadar berhasil, tetapi juga berdamai.
Kalau Anda ingin memperdalam praktik ini secara terstruktur—mulai dari latihan hening, kerangka keputusan, hingga pembiasaan harian—kita mengupasnya rapi di Prommunity. Datanglah, belajar pelan-pelan, dan biarkan intuisi Anda punya ruang.
Puisi
Runtuh nya Ego, Pulang ke Cahaya
Di ruang sunyi dalam dada,
Dua suara bicara, diam-diam bersuara.
Yang satu berteriak, menggema cepat,
Yang satu berbisik, lembut tapi kuat.
Ego berkata: “Ambil semua yang tampak gemilang, Buktikan dirimu, sebelum dunia memandangmu hilang.”
Ia penuh logika, penuh hitungan,
Tapi hatiku terasa kehilangan.
Intuisi berkata: “Tak semua yang bersinar itu terang, Dengarkan aku, meski jalan ini tampak kurang.”
Ia tak memaksa, hanya mengajak, Namun damainya membuat langkah tak tersesat.
Ego adalah topeng dari masa lalu,
Luka yang menyamar jadi ambisi semu.
Intuisi adalah nyala dari jiwa yang lurus,
Suara Tuhan yang datang tanpa harus.
Ego berlari karena takut tertinggal,
Intuisi berjalan karena yakin pada bekal.
Ego haus akan pengakuan,
Intuisi rindu akan keutuhan.
Ego menginginkan dunia di genggaman,
Namun kosong di saat keramaian.
Intuisi mengajak menyelam ke dalam,
Menemukan makna di balik keheningan.
Ego memintaku bergegas dan membuktikan,
Intuisi mengajarku menunggu dan merasakan.
Ego menuntut jawaban sekarang,
Intuisi tahu: kebenaran butuh waktu yang panjang.
Tak mudah memang meredam gemuruh kepala,
Saat dunia memuja yang cepat dan megah rupa.
Tapi kupercaya pada cahaya yang perlahan,
Yang menuntunku pulang ke kedalaman
Maka jika hari ini aku bimbang dan terombang,
Tak akan kupaksa langkah dengan gemetar.
Kupeluk saja sunyi, kupeluk rasa gentar,
Sampai suara jiwaku kembali terdengar.
Sebab aku tahu,
Dalam pertarungan diam antara ego dan intuisi,
Yang menang bukan yang paling keras berteriak,
Tapi yang paling jujur membimbing langkah