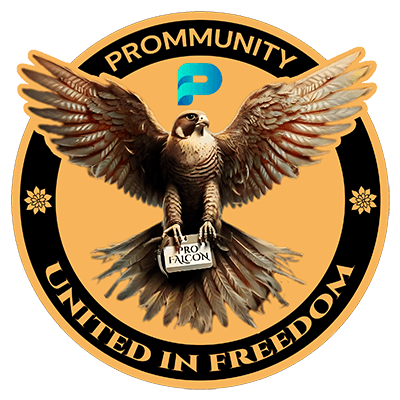Aku hanyalah pelaut muda
yang suatu hari diundang naik ke atas bahtera
oleh seorang nakhoda agung.
Ia bukan sekadar pemimpin kapal,
ia adalah lautan yang jernih,
yang gelombangnya tak pernah memukul tanpa alasan,
yang hembusan anginnya selalu membawa arah pulang.
Darinya, aku belajar membaca bintang,
mendengar bahasa ombak,
dan memahami bahwa samudra bukan sekadar air—
ia adalah cermin yang memantulkan cahaya langit
ke dalam hati.
Namun pada suatu malam,
langit memperlihatkan padaku sebuah peta
yang tak pernah kulihat sebelumnya.
Rutenya aneh, jalannya berliku,
tak sesuai garis yang kupahami.
Tetapi selama tanganku masih menggenggam tali kemudi
bersama Sang Nakhoda,
aku tetap percaya
bahwa ia tahu arah yang dituju.
Hari-hari berlalu,
ombak semakin tinggi,
badai datang tanpa tanda.
Sejenak aku meragukan:
Apakah ia masih tahu jalan?
Atau kapal ini sedang tersesat?
Logikaku mulai mendebat arah angin,
meragukan setiap tarikan layar.
Hingga aku lelah berperang dengan pikiranku sendiri
dan memilih bersujud di geladak,
berbisik pada Pemilik Lautan.
Di situlah jawabannya datang
seperti fajar yang memecah malam:
“Nakhodamu tak berpaling dari-Ku.
Ia berlayar di jalur yang Aku restui.
Tetaplah di atas kapal ini.”
Maka aku mengerti—
bahwa badai bukanlah tanda kita salah,
melainkan ujian agar kita lebih erat berpegangan.
Selama Sang Nakhoda setia pada kompas langit,
aku, sebagai pelaut,
akan meniti gelombang bersamanya
hingga pelabuhan terakhir—
tempat lautan dan cahaya
bertemu dalam damai abadi.